oleh Muhammad Faqihna Fiddin
Pernahkah kamu bertanya-tanya: “Kenapa sih, setiap kali aku hampir berhasil, aku justru menghancurkan semuanya?” Atau mungkin: “Kenapa aku selalu menunda pekerjaan penting, padahal aku tahu itu merugikan diriku sendiri?” Fenomena ini disebut self-sabotage atau perilaku menghambat diri sendiri.
Di permukaan, self-sabotage tampak aneh dan masokis. Seolah-olah kita sengaja menyakiti diri karena membenci diri sendiri, kurang percaya diri, atau tidak punya kemauan. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, self-sabotage jarang sekali lahir dari kebencian pada diri. Sebaliknya, ia justru merupakan cara pikiran bawah sadar kita memenuhi kebutuhan psikologis tertentu. Inilah yang disebut unconscious needs — kebutuhan tak sadar yang diam-diam mengendalikan pilihan dan tindakan kita.
Artikel ini akan membedah fenomena self-sabotage dengan kacamata kebutuhan tak sadar: apa itu, bagaimana cara kerjanya, apa saja bentuknya, serta bagaimana kita bisa membongkar dan mengubah pola ini.
Apa Itu Self-Sabotage?
Mengutip dari buku “The Mountain is You” secara sederhana, self-sabotage adalah pola perilaku atau kebiasaan yang secara langsung menghalangi tujuan dan kebahagiaan kita sendiri. Bentuknya bisa beragam:
- Menunda pekerjaan (prokrastinasi).
- Mengabaikan kesehatan.
- Menghabiskan uang berlebihan padahal sedang berhemat.
- Merusak hubungan yang sebenarnya sehat.
- Keluar dari peluang tepat sebelum sukses datang.
Self-sabotage biasanya bukan keputusan sadar. Hampir tidak ada orang yang bangun pagi dan berkata: “Hari ini aku mau merusak karierku sendiri.” Justru sebaliknya, perilaku itu muncul otomatis, seolah-olah ada “rem tangan psikologis” yang menarik kita kembali saat kita mencoba melaju.
Mengapa Kita Melakukannya? Masuk ke Dunia Kebutuhan Tak Sadar
Untuk memahami self-sabotage, kita perlu memahami kebutuhan psikologis. Manusia punya kebutuhan dasar: rasa aman, koneksi sosial, harga diri, otonomi, dan seterusnya. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi secara sehat, pikiran bawah sadar kita akan mencari cara lain — meskipun caranya justru kontraproduktif.
Di sinilah lahir self-sabotage. Ia bukan sekadar “kesalahan” atau “kemalasan,” melainkan strategi bawah sadar untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terlihat.
Contoh:
- Seseorang menunda pekerjaan penting. Di permukaan, terlihat malas. Tapi di kedalaman, ia memenuhi kebutuhan akan rasa aman dari kegagalan. Jika ia gagal karena kurang waktu, itu terasa lebih aman daripada gagal setelah berusaha maksimal.
- Seseorang terus memilih pasangan yang toxic. Secara logika, ini merugikan. Namun, pola itu memenuhi kebutuhan akan familiaritas: chaos terasa lebih “normal” karena dulu ia tumbuh di lingkungan penuh konflik.
Daftar Kebutuhan Tak Sadar yang Sering Mendorong Self-Sabotage
Berikut adalah kebutuhan tak sadar paling umum yang biasanya bersembunyi di balik perilaku self-sabotage:
- Kebutuhan akan Rasa Aman (Safety/Protection) Menghindari risiko, kritik, atau penolakan. Lebih baik tidak mencoba daripada terluka. Misal, Rina selalu menolak promosi kerja dengan alasan “belum siap.” Padahal, dia punya kemampuan. Tanpa sadar, ia takut jika menerima promosi lalu gagal, maka ia akan lebih terluka. Jadi, menolak promosi memberinya rasa aman dari kemungkinan kegagalan.
- Kebutuhan akan Kontrol/Prediktabilitas Mengatur skenario agar hasil terasa bisa ditebak, meskipun negatif. Dengan cara ini, kita merasa “tetap pegang kendali.” Misal, Budi sering mengakhiri hubungan lebih dulu setiap kali pacarnya mulai serius. Ia lebih memilih memutuskan ketimbang “ditinggalkan.” Dengan begitu, meskipun sakit, ia merasa tetap memegang kendali atas hasil akhirnya.
- Kebutuhan akan Validasi/Perhatian Mendapat pengakuan atau simpati dari orang lain melalui kesulitan. Misal, Dwi sering mengeluh tentang betapa stresnya pekerjaannya, tapi tidak berusaha mencari solusi. Tanpa sadar, ia mendapat perhatian dan simpati dari teman-temannya setiap kali ia mengeluh, dan itulah “hadiah” tersembunyi dari perilakunya.
- Kebutuhan akan Kenyamanan/Familiaritas Memilih pola lama yang tidak sehat karena sudah terbiasa. Hal baru, meskipun lebih baik, terasa menakutkan. Misal: Andi terus kembali ke hubungan yang toxic dengan mantan pacarnya. Secara logika, dia tahu hubungan itu merusak. Namun, pertengkaran dan drama terasa “normal” karena sejak kecil ia terbiasa melihat orang tuanya bertengkar.
- Kebutuhan untuk Menghindari Emosi Menyakitkan Numbing atau kabur dari rasa malu, sedih, marah, atau kesepian dengan cara-cara destruktif. Misal, Sari selalu menghabiskan malam dengan binge-watching atau ngemil berlebihan setiap kali merasa kesepian. Alih-alih menghadapi rasa sepi, ia memilih “menumpulkan” emosinya dengan distraksi sementara.
- Kebutuhan Konsistensi dengan Self-Image Jika kita percaya “aku tidak pantas sukses,” maka kita akan secara tak sadar bertindak agar keyakinan itu terbukti benar. Misal, Agus percaya dirinya “bukan orang pintar.” Saat diberi kesempatan ikut lomba debat, ia sengaja tidak berlatih maksimal. Ketika kalah, ia bisa berkata, “Ya wajar, aku memang nggak pintar,” sehingga keyakinan lamanya tetap terbukti benar.
- Kebutuhan akan Otonomi/Kebebasan Memberontak terhadap aturan atau ekspektasi, meskipun akhirnya menyakiti diri. Misal, Maya merasa dikekang setiap kali manajernya memberi target detail. Ia lalu sengaja melanggar deadline untuk membuktikan bahwa ia bebas menentukan jalannya sendiri, meskipun konsekuensinya merugikan dirinya.
- Kebutuhan akan Koneksi/Belonging Menyesuaikan diri dengan kelompok atau keluarga, bahkan jika itu berarti mengecilkan potensi sendiri. Misal, Fajar berasal dari keluarga sederhana. Ketika mulai sukses di bisnis, ia justru menahan diri untuk tidak terlalu menonjol karena takut membuat saudaranya merasa minder atau menjauh. Ia secara tidak sadar lebih memilih koneksi dengan keluarga daripada pencapaian pribadi.
- Kebutuhan akan Kelegaan dari Tekanan Menurunkan standar melalui kegagalan dini agar ekspektasi orang lain (atau diri sendiri) juga turun. Misal, Lina selalu menyerah di tengah jalan saat menulis skripsi. Dengan cara itu, ia bisa mengatakan “Aku gagal karena malas,” bukan karena tidak mampu secara intelektual. Hal ini menurunkan ekspektasi orang lain sekaligus mengurangi tekanan dalam dirinya.
Contoh Kasus: Prokrastinasi
Mari kita telusuri salah satu contoh paling umum: menunda pekerjaan (prokrastinasi).
- Perilaku: menunda-nunda tugas penting hingga deadline mepet.
- Di permukaan: terlihat malas, kurang disiplin, atau tidak serius.
- Kebutuhan tak sadar: menghindari kegagalan. Jika gagal karena tidak punya waktu, itu terasa lebih “aman” daripada gagal setelah mengerahkan usaha penuh.
- Cara sehat untuk mengganti: membangun keberanian menghadapi kemungkinan gagal, serta belajar melihat kegagalan sebagai informasi, bukan identitas.
Bagaimana Mengenali Kebutuhan Tak Sadar Kita Sendiri?
Ada beberapa langkah detektif psikologis yang bisa kita lakukan:
- Identifikasi Pola Sabotase Tanyakan: “Di area mana aku sering menghambat diriku sendiri?”
- Cari Manfaat Tersembunyi “Apa yang diam-diam aku dapatkan dari perilaku ini?” Apakah itu rasa aman, perhatian, atau kontrol?
- Lacak ke Masa Lalu “Kapan aku pertama kali belajar bahwa pola ini lebih aman?” Sering kali jawabannya ada di pengalaman masa kecil atau trauma lama.
- Uji dengan Pertanyaan Kontra “Apakah pola ini benar-benar melindungiku sekarang, atau justru menjebakku?”
Jalan Keluar: Mengganti Pola, Bukan Sekadar Melawan
Kesalahan terbesar banyak orang adalah mencoba mengatasi self-sabotage dengan kemauan keras (willpower) semata. Masalahnya: jika akar permasalahannya ada pada kebutuhan tak sadar, maka sekadar “memaksa diri” hanya akan menimbulkan resistensi.
Kuncinya adalah mengganti cara pemenuhan kebutuhan itu dengan strategi yang lebih sehat.
- Jika sabotase muncul karena kebutuhan rasa aman → bangun resiliensi: belajar bahwa kita bisa bangkit dari kegagalan.
- Jika muncul dari kebutuhan validasi → latih self-compassion dan cari dukungan sehat, bukan drama.
- Jika muncul dari kebutuhan familiaritas → perlahan biasakan diri dengan “zona nyaman baru” yang lebih sehat.
Reinventing Self-Image
Self-sabotage juga erat kaitannya dengan citra diri (self-image). Jika kita percaya bahwa kita tidak pantas sukses, maka segala tindakan kita akan “disetel” agar keyakinan itu benar.
Maka, salah satu pekerjaan besar adalah menciptakan ulang narasi diri:
- Mengubah dialog internal dari “aku pasti gagal” menjadi “aku boleh mencoba dan belajar.”
- Menyadari bahwa masa lalu menjelaskan diri kita, tapi tidak menentukan masa depan.
Keterampilan yang Membantu
Ada beberapa “otot psikologis” yang perlu dilatih untuk keluar dari pola sabotase:
- Kecerdasan emosional (emotional intelligence): kemampuan mengenali, memahami, dan mengatur emosi sendiri.
- Resiliensi: kemampuan bangkit dari kegagalan atau kesulitan.
- Mindfulness: kesadaran penuh terhadap pola pikiran tanpa langsung menilai.
- Self-compassion: memperlakukan diri dengan kebaikan alih-alih dengan kritik kejam.
Dari Musuh Menjadi Sekutu
Self-sabotage bukan tanda kita rusak atau lemah. Ia adalah mekanisme adaptasi lama yang dulu mungkin menyelamatkan kita, tapi kini sudah tidak relevan. Dengan menyadari kebutuhan tak sadar di baliknya, kita bisa berhenti melihat diri sebagai musuh, dan mulai menata ulang strategi hidup kita.
Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menghapus kebutuhan itu, tapi memenuhinya dengan cara yang lebih sehat, produktif, dan selaras dengan tujuan hidup kita.
Sumber: Buku the Mountain is You





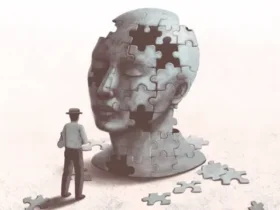
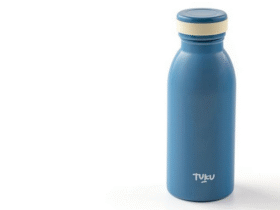
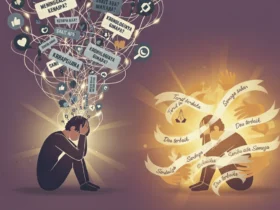


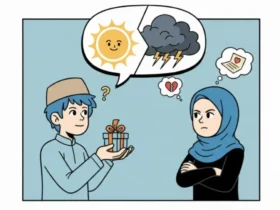
Leave a Reply
View Comments