Oleh Muhammad Faqihna Fiddin
Pada awal Agustus 2025, sebuah bendera yang biasanya hanya muncul dalam halaman manga atau layar anime tiba-tiba berkibar di jalanan Indonesia. Bendera itu bergambar tengkorak bertopi jerami, simbol kru bajak laut Luffy dalam One Piece.
Banyak orang terkejut sekaligus bingung: mengapa ikon fiksi dipakai sebagai tanda protes? Pemerintah bereaksi hati-hati, sebagian pejabat menilai ini sekadar ekspresi anak muda, sebagian lain menganggapnya tanda ketidakpuasan yang serius. Tak lama berselang, bendera yang sama juga muncul di Nepal, dibawa oleh para demonstran yang menentang kebijakan pemerintah mereka. Fenomena ini seakan menunjukkan bahwa simbol budaya populer tidak lagi terbatas pada ruang hiburan, tetapi sudah masuk ke ranah politik nyata.
Fenomena serupa sebenarnya sudah terjadi di banyak tempat. Thailand, pada 2014, mengalami kudeta militer. Dalam situasi penuh ketegangan itu, anak-anak muda turun ke jalan sambil mengangkat tiga jari ke udara, meniru salam perlawanan dalam film The Hunger Games. Tiba-tiba, sebuah gestur fiksi menjadi alat komunikasi politik yang berbahaya. Militer sampai melarang salam itu karena dianggap lambang perlawanan.
Sementara itu, di dunia maya, buah semangka mendadak jadi simbol solidaritas untuk Palestina. Warna merah, hijau, putih, dan hitam pada buah itu dipandang mewakili bendera Palestina, sehingga gambar semangka dipakai untuk menghindari sensor sekaligus menyebarkan pesan dukungan. Semua contoh ini memperlihatkan bagaimana budaya populer bisa berubah menjadi bahasa politik baru.
Mengapa simbol-simbol seperti ini bisa begitu kuat? Alasannya sederhana tapi dalam. Pertama, simbol populer mudah dikenali. Orang yang menonton One Piece tahu bahwa Luffy adalah tokoh yang melawan tirani. Saat bendera Luffy berkibar, pesan “melawan penguasa” langsung tertangkap tanpa perlu penjelasan panjang. Kedua, simbol visual lebih mudah menyebar daripada slogan atau manifesto. Di media sosial, gambar, meme, atau emoji bisa viral dalam hitungan jam.
Ketiga, simbol membawa emosi. Mereka bukan hanya tanda kosong, tetapi juga cerita dan perasaan. Orang merasa lebih dekat dengan aksi protes jika simbol yang dipakai adalah tokoh atau cerita yang mereka cintai. Namun, di sinilah jebakannya: simbol mudah menyederhanakan masalah. Tuntutan politik bisa larut dalam estetika yang keren, sementara substansi sebenarnya kabur.
Ada anggapan yang sering muncul: kalau anak muda memakai simbol budaya pop, berarti mereka tidak serius berpolitik, hanya ikut-ikutan tren. Pandangan ini tampak logis, tetapi tidak sepenuhnya benar. Simbol bisa menjadi pintu masuk bagi mereka yang awalnya apatis. Melalui meme atau bendera fiksi, mereka mulai memperhatikan isu politik, ikut berdiskusi, lalu terlibat lebih jauh. Tetapi di sisi lain, simbol memang rawan dikosongkan. Tanpa agenda yang jelas, gerakan hanya berhenti pada tampilan. Ini sebabnya simbol disebut ambivalen: bisa membuka ruang partisipasi, tapi juga bisa membuat gerakan dangkal.
Kalau kita melihat ke belakang, penggunaan simbol dalam politik bukanlah hal baru. Pada 1960-an, wajah Che Guevara dipakai di kaus dan poster di seluruh dunia sebagai simbol revolusi. Beberapa dekade kemudian, topeng Guy Fawkes dari film V for Vendetta menjadi ikon gerakan Occupy Wall Street dan kelompok Anonymous. Sekarang, bendera One Piece atau salam tiga jari menggantikan peran itu. Bedanya, di era internet, penyebaran simbol jauh lebih cepat. Maknanya pun bisa berubah-ubah tergantung bagaimana warganet menafsirkannya. Sebuah gambar bisa dilihat sebagai simbol keberanian, tetapi juga bisa dipelesetkan jadi lelucon atau komoditas.
Simbol populer juga punya fungsi taktis. Ia memberi ruang untuk “bersembunyi.” Di negara dengan sensor ketat, protes lewat bendera bajak laut atau salam dari film jauh lebih sulit ditindak langsung dibandingkan poster yang berisi kata “turunkan presiden.” Demonstran bisa berkelit: “ini hanya ekspresi budaya, bukan politik.” Tapi negara tidak bodoh. Di Thailand, salam tiga jari akhirnya dilarang, dan orang-orang yang menggunakannya ditangkap. Ini membuktikan bahwa pemerintah bisa melihat simbol fiksi sebagai ancaman nyata, terutama ketika simbol itu berhasil menggerakkan massa.
Yang menarik, budaya populer bersifat lintas batas. Produk Jepang, Hollywood, atau Korea bisa menjadi bahasa bersama bagi anak muda di berbagai negara. Itulah mengapa simbol One Piece bisa dipahami di Indonesia maupun Nepal. Ada globalisasi emosi politik di sini: generasi yang tumbuh bersama komik, anime, dan film blockbuster punya “kamus simbol” yang sama. Namun, simbol tidak selalu diterjemahkan dengan cara yang sama di tiap tempat. Makna lokal tetap menentukan. Di satu negara, bendera One Piece bisa dipandang sebagai tanda perlawanan; di tempat lain, bisa dianggap sekadar kreativitas anak muda.
Mengutip dari BBC Indonesia, pengamat budaya pop, Hikmat Darmawan, menilai penggunaan simbol atau istilah dari ranah budaya populer dalam gerakan sosial bukanlah hal baru. Praktik “meminjam” itu kerap dipakai sebagai strategi komunikasi, bukan sekadar karena keterbatasan atau rasa takut. Dengan mengadopsi simbol yang sudah akrab di kalangan publik, pesan kritik bisa menembus audiens yang lebih luas. “Sering kali tujuannya bukan untuk menghindari represi, melainkan supaya pesan lebih mudah diterima banyak orang,” ujarnya.
Kita bisa melihat hal yang sama di Hong Kong, ketika gerakan payung kuning lahir pada 2014. Awalnya, payung hanyalah benda sehari-hari yang dipakai demonstran untuk melindungi diri dari gas air mata. Tetapi dalam sekejap, payung berwarna kuning menjadi simbol internasional untuk perjuangan demokrasi di Hong Kong. Ia muncul dalam mural, media sosial, bahkan pameran seni. Simbol sederhana itu menjadi cara masyarakat global ikut merasakan perjuangan anak muda Hong Kong. Hal ini menunjukkan bahwa simbol tak selalu lahir dari dunia hiburan; benda sehari-hari pun bisa berubah jadi tanda perlawanan, asalkan mengandung cerita emosional yang kuat.
Belarus memberikan contoh lain. Pada protes besar tahun 2020 melawan Presiden Alexander Lukashenko, banyak meme yang dipakai untuk menyindir pemerintah. Salah satu yang populer adalah penggunaan karakter Pepe the Frog. Awalnya, Pepe adalah meme netral di internet, kemudian dipolitisasi di Amerika oleh kelompok sayap kanan, lalu di Belarus dipakai kembali dengan makna berbeda: bukan lambang ekstremisme, melainkan simbol ejekan terhadap rezim otoriter. Perjalanan Pepe menunjukkan betapa lenturnya simbol di era digital: maknanya bisa berbalik 180 derajat, tergantung siapa yang memakainya dan dalam konteks apa.
Di Amerika Serikat, fenomena simbol politik juga terlihat jelas. Topi merah bertuliskan “Make America Great Again” (MAGA) menjadi simbol utama pendukung Donald Trump. Tetapi dalam banyak aksi protes, topi serupa dipakai dengan tulisan berbeda untuk menyindir Trump. Misalnya, ada topi parodi dengan tulisan “Make America Gay Again” atau “Make Racism Wrong Again.” Simbol yang sama bisa dipakai dua kubu dengan maksud berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa simbol adalah arena perebutan makna: siapa yang lebih kreatif dan lebih cepat menyebarkan tafsirnya, dialah yang menguasai narasi.
Pertanyaan ideologis pun muncul. Apakah semua ini berarti ideologi besar sudah mati? Tidak juga. Generasi muda memang cenderung menolak doktrin kaku. Mereka lebih suka politik yang cair, berbasis pengalaman dan solidaritas sesaat. Tetapi ini bukan nihilisme. Justru ada bentuk baru ideologi: fragmen-fragmen visual yang membangun solidaritas instan. Jika dulu ideologi disampaikan lewat buku dan manifesto, sekarang ia muncul lewat meme, emoji, atau bendera anime. Masalahnya, fragmen ini tidak otomatis menjadi program politik. Perlu ada jembatan agar energi simbolik bisa berubah menjadi aksi nyata. Tanpa jembatan itu, protes hanya jadi pesta simbol.
Ada juga persoalan etis. Simbol budaya punya pemilik dan penggemar. Banyak fans One Piece di Indonesia, misalnya, merasa risih simbol Luffy dipakai untuk protes. Mereka takut makna cerita asli dipelintir. Negara pun serba salah. Jika dilarang, bisa menimbulkan kemarahan dan justru memperkuat gerakan. Jika dibiarkan, simbol itu bisa menjadi senjata untuk mengkritik pemerintah. Situasi ini memperlihatkan bahwa politik simbolik selalu bermain di wilayah abu-abu: siapa berhak memaknai, siapa berhak mengontrol.
Masalah lain adalah keberlanjutan. Simbol bisa menarik ribuan orang dalam sekejap, tapi tanpa organisasi, gerakan cepat padam. Simbol membangkitkan perhatian, tetapi hanya strategi dan struktur yang bisa mengubahnya menjadi kebijakan. Banyak gerakan berhenti di level “ramai di media sosial” tanpa hasil nyata. Inilah tantangan utama politik di era meme: bagaimana mengubah viralitas menjadi perubahan.
Pada akhirnya, fenomena ini memaksa kita memandang politik dengan cara baru. Politik tidak lagi hanya berlangsung di gedung parlemen atau dalam rapat partai, tetapi juga di ruang budaya populer. Meme, film, komik, dan bahkan buah-buahan bisa menjadi bahasa politik. Hiburan dan resistensi kini saling bertemu.
Apakah ini tanda kemerosotan politik? Tidak selalu. Ini justru tanda perubahan. Politik generasi sekarang lebih visual, lebih cair, dan lebih cepat. Simbol mungkin tidak memberikan jawaban, tetapi mereka membuka pintu partisipasi. Tugas berikutnya adalah memastikan pintu itu mengarah ke jalan yang jelas, bukan ke ruang hampa.
Bendera One Piece, salam tiga jari, payung kuning di Hong Kong, meme Pepe di Belarus, atau topi merah di Amerika menunjukkan satu pola besar: politik hari ini tidak lagi hanya soal orasi panjang, tetapi juga soal bahasa visual yang mudah dipahami semua orang. Politik simbolik di era meme adalah tanda bahwa demokrasi sedang bertransformasi. Ia bisa rapuh jika hanya berhenti pada estetika, tapi bisa kuat jika dijadikan jembatan menuju aksi nyata.
(Sumber: BBC Indonesia, CNN Indonesia, Kompas, Tempo, The Staits Time)





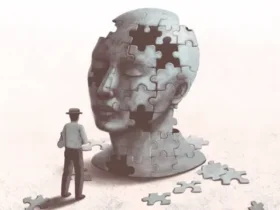
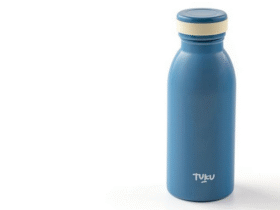




Leave a Reply
View Comments