Bicara soal kemerdekaan, pikiran kita seringnya langsung melayang ke momen 17 Agustus. Bayangan bendera merah putih berkibar, lagu kebangsaan, lomba makan kerupuk, sampai cerita perjuangan pahlawan kemerdekaan.
Tapi di akhir-akhir ini, buat banyak anak muda, makna kemerdekaan udah jauh lebih kompleks dari sekadar lepas dari penjajah fisik. Kemerdekaan jadi sesuatu yang lebih personal, lebih terkait sama kehidupan sehari-hari, dan sering kali punya definisi yang berbeda-beda di setiap kepala.
Sidqi, 34 tahun, yang bekerja di bagian legal & compliance di sebuah perusahaan swasta, punya pandangan yang cukup tajam soal ini. Baginya, kemerdekaan hari ini adalah kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih jalan hidup tanpa dibatasi diskriminasi atau ketidakadilan. Bukan cuma itu, ia melihat kemerdekaan sebagai kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa terhalang oleh latar belakang sosial, ekonomi, atau wilayah. Artinya, merdeka itu ketika setiap orang bisa berlari di lintasan yang sama, tanpa ada yang sengaja diperlambat atau dijegal hanya karena mereka berbeda.
Robby, 29 tahun, karyawan swasta lulusan Sastra Inggris, punya definisi yang nyentuh aspek lain. Buat dia, kemerdekaan berarti bebas mengemukakan pendapat tanpa ancaman, dan merdeka secara finansial. “Percuma demokrasi kalau gaji nggak layak sementara biaya hidup dan pajak makin tinggi,” ujarnya. Baginya, bisa hidup di negara demokrasi itu ideal, tapi akan terasa hampa kalau kenyataannya masih melihat kesenjangan signifikan terutama pada bidang pendidikan.
Dua perspektif ini, walaupun datang dari latar belakang yang berbeda, punya benang merah yang jelas: kemerdekaan di mata anak muda bukan sekadar simbol atau seremoni, tapi soal hidup layak, suara yang didengar, dan kesempatan yang setara.
Tapi kalau kita mulai ngomongin soal kondisi Indonesia saat ini, atmosfernya langsung bergeser. Sidqi mengaku optimis tapi optimis hati-hati. Dia melihat banyak anak muda kreatif, kritis, dan aktif di berbagai bidang, dari teknologi sampai seni dan kewirausahaan. Ada semangat yang tumbuh, inovasi yang mekar.
Tapi ia juga sadar masih banyak masalah klasik yang nggak kunjung selesai: korupsi yang membandel, ketimpangan yang nyata, kebijakan yang kadang lebih menguntungkan segelintir orang daripada rakyat kebanyakan. Optimisme yang ia punya seperti seseorang yang mau menyeberangi jembatan gantung: semangat melangkah, tapi tetap waspada melihat tali yang mulai aus.
Robby justru memandang dari sisi lain. Dia cenderung pesimis, karena dua hal yang ia anggap inti kemerdekaan—kebebasan berpendapat dan kemandirian finansial—menurutnya makin jarang terlihat. Ia melihat situasi di mana anak muda boleh bicara, tapi apakah pendapat mereka benar-benar didengar atau hanya lewat seperti angin? Ia mengibaratkan kondisi sekarang seperti punya mikrofon yang nyala, tapi speakernya dicabut.
Politik jadi topik berikutnya yang nggak bisa dihindari. Sidqi menggambarkannya sebagai sesuatu yang dinamis, tapi terlalu sering terjebak dalam perebutan kekuasaan ketimbang fokus menyelesaikan masalah rakyat. Memang, ada kemajuan soal keterbukaan informasi, tapi praktik transaksional, polarisasi, dan lemahnya integritas sebagian pejabat bikin banyak orang mulai muak.
Robby bahkan lebih blak-blakan. Menurutnya, politik Indonesia sekarang sulit didefinisikan—bukan demokrasi penuh, bukan komunis, bukan juga liberal. “Speechless,” begitu katanya. Ia nggak mengikuti politik secara intens, tapi media sosial membuatnya mau nggak mau terpapar berita yang bikin dia mengernyitkan dahi.
Namun, ada kesamaan pandangan yang mencolok. Baik Sidqi maupun Robby sepakat bahwa masalah terbesar bukan cuma soal oknum, tapi soal sistem. Mereka berdua punya momen-momen yang bikin sadar bahwa ada yang salah besar. Sidqi mengingat berita korupsi di sektor kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam—tiga hal yang jadi kebutuhan paling mendasar bagi rakyat. Robby menyoroti kebijakan yang terasa “nggak masuk akal” dan lembaga penegak hukum yang seharusnya melindungi rakyat tapi malah terkesan berpihak pada pelanggar. Rasanya seperti punya rumah yang bocor di semua sisi, tapi tukang yang dipanggil malah sibuk foto-foto untuk pamer di media sosial.
Pertanyaannya, kalau kita tahu masalahnya, apa yang akan kita lakukan kalau punya kesempatan memimpin? Sidqi tanpa ragu menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama. Pendidikan berkualitas gratis akan melahirkan generasi yang cerdas dan kritis, sementara kesehatan yang terjangkau akan membuat rakyat lebih produktif. Robby, meski punya pandangan pesimis soal politik, ternyata sependapat. Ia menekankan pentingnya menaikkan gaji tenaga pendidik dan tenaga medis, serta membuat seleksi ketat agar kualitas SDM benar-benar terjaga. Di sini terlihat bahwa walaupun cara pandang mereka terhadap situasi berbeda, mereka punya titik temu soal prioritas yang harus diambil.
Lalu, bagaimana peran generasi muda di semua ini? Sidqi menekankan pentingnya melek informasi dan berpikir kritis. Ia mengajak anak muda untuk nggak cuma protes di media sosial, tapi juga ikut terlibat langsung di organisasi atau komunitas. Gunakan keahlian masing-masing untuk memberi kontribusi nyata—entah lewat teknologi, edukasi, atau karya.
Robby menambahkan pesan agar anak muda meningkatkan value diri, banyak membaca, dan melek politik supaya nggak gampang dibodohi. Dan kalau sudah terjun ke pemerintahan atau posisi pengambil kebijakan, mempertahankan kejujuran dan keadilan itu wajib, karena banyak nyawa bergantung pada keputusan yang diambil.
Soal fenomena bendera One Piece yang saat ini viral merupakan kritik rakyat atas pemerintahan yang sering mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat. Sidqi, dengan kacamata hukumnya, menjelaskan bahwa secara umum bendera itu nggak otomatis melanggar hukum karena hanya simbol fiksi. Tapi ia mengingatkan ada batasannya yaitu jangan dimodifikasi menyerupai bendera negara, jangan dipakai untuk makar, dan jangan dikibarkan di acara resmi kenegaraan. Kalau cuma buat hobi atau cosplay, aman-aman saja. Robby punya pandangan yang lebih santai.
Menurutnya, bendera itu bisa jadi cerminan kondisi negara kalau orang paham ceritanya. “Sah-sah aja, toh kita negara demokrasi kan? Asal tetap menjunjung tinggi dan tidak melecehkan bendera merah putih,” ujarnya. Fenomena ini mungkin terdengar ringan, tapi sebenarnya menggambarkan dilema yang sering dihadapi anak muda zaman sekarang: antara kebebasan berekspresi dan batasan yang ditetapkan hukum serta norma sosial.
Dari semua obrolan ini, terasa jelas bahwa anak muda hari ini punya idealisme yang besar, tapi juga nggak menutup mata pada realitas yang kadang pahit. Ada yang optimis hati-hati, ada yang pesimis realistis. Keduanya sama-sama paham bahwa perubahan nggak bakal datang dari langit, melainkan harus diupayakan lewat partisipasi, integritas, dan keberanian terjun langsung ke medan yang sering kali kotor dan penuh risiko.
Kemerdekaan di zaman sekarang memang sudah bukan lagi sekadar upacara tahunan. Ia adalah proses panjang untuk memastikan setiap orang bisa hidup layak, berpikir bebas, dan punya kesempatan yang sama. Ia bukan hadiah yang sudah selesai dibungkus sejak 1945, tapi pekerjaan rumah yang harus terus dikerjakan. Ada baiknya kita memastikan simbol merah putih itu benar-benar bermakna di kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan cuma tentang apa yang kita rayakan, tapi tentang apa yang kita perjuangkan setiap hari.





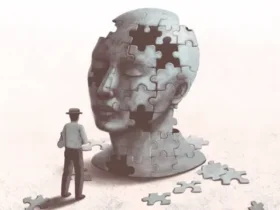
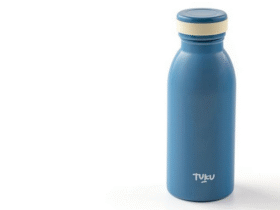




Leave a Reply
View Comments